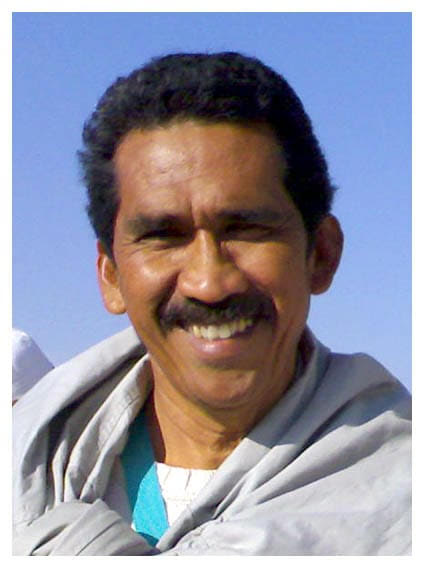Sabang Morai
Oleh: Darmansyah
Sabang adalah Indonesia?
Sepertinya saya sulit diyakinkan bahwa Sabang itu adalah Indonesia Di otak saya Sabang itu nggak pernah punya persambungan dengan kata Merauke-nya.
Yang kemudiannya lanjut dengan namanya Indonesia.
Sabang–Mmerauke itu bagi saya hanya jargon. Jargon yang sudah lama mengalami inflasi. Sudah terdegradasi.
Seperti terdegradasinya penggalan lagu: dari Sabang sampai Merauke dan seterusnya… dan seterusnya…
Bukan hanya saya. Anak-anak PAUD pun hang ..hing..heng… dengan persambungan syair yang kata-katanya: berjejer pulau-pulau… dan itulah…
Nggak percaya?
Coba alunkan syairnya ke mereka. Saya memastikan mereka akan bengong untuk menyambung lanjutan bait syairnya atau kepayahan hingga melelahkan untuk melantunkan dendang irama dengungnya… ng-ng-ng……
Bagi saya sejak menyadari Indonesia dalam syair..”sekali merdeka tetap merdeka”… harga tawarnya bukan berarti Sabang itu harus dipasangkan dengan Merauke-nya. Sabang itu bagi saya tetap bebas. Berdiri sendiri.
Seperti pelabuhan bebas. Perdagangan bebas. Dan ia berada dalam jangkauan kebebasan. Semua itu dulunya diakomodir dalam regulasi kepabeanan yang bebas dari negeri bernama Indonesia.
Regulasi ini sudah ada sejak dulu. Sejak saya masih di arash langit…
Sejak “Sabang Maatschapay”. Sejak Rotterdam Lyoid dan Nederland Handel mengelola Sabang sebagai sebuah otorita. Sejak otorita itu berkantor di teluk indah itu.
Otorita yang membangun dermaga untuk kapal-kapal ukuran jumbo dan memasang derek dengan tonase tinggi serta membangun macam-macam.
Seperti membangun area penimbunan batubara untuk bahan bakar kapal yang berlayar ke Eropa lewat Tanjung Harapan. Melintas Pasifik untuk menjangkau Amerika atau pun Asia Timur.
Bukan membangun penimbunan cangkang sawit.
Itulah Sabang yang di bawah bendera sebuah matschapay.
Tiga bulan lalu saya ke Sabang. Kunjungan untuk kesekian puluh kalinya. Saya nggak berani menaikkan hitungannya ke angka seratusan. Itu kunjungan terakhir.
Di kunjungan itu saya membawa empat teman investor. Naik speedboat selama satu jam dari Ulee Lheue. Dari pelabuhan kecil di ceruk muara yang bersebelahan dengan sebuah masjid.
Masjid yang menjadi ikon usai tsunami karena tetap tegak sebagai lambang keutuhan negeri ujong donya ini. Masjid yang nggak disapu hambalang laut. Masjid yang nggak retak oleh amblasnya tanah di perut samudera sana.
Saya sengaja memilih rute penyeberangan speedboat carteran yang menjadi tumpangan kami mengambil jalan memutar Weh. Tidak tembak langsung dan merapat ke Balohan sebagaimana fery yang menghubungi daratan dengan pulau itu.
Boat kecil berkecepatan tinggi itu mengambil jalan memutar untuk sampai ke pelabuhan milik matschapay. Pelabuhan Sabang. Pelabuhan di ceruk perut pulau. Pulau Weh.
Di di dermaga pelabuhan itu Sabang masih memesona. Masih cantik sekali dengan perahu-perahu nelayan yang menari diayun nyanyian kecipak gelombang kecil tiupan angin samudera.
Di pinggiran dermaga tersisa gudang-gudang beratapkan seng.
Depan pelabuhan ada masjid dengan kubah mengkilat, menara warna putih hijau, juga rumah-rumah yang bersusun di setiap trap tanah undukan yang dicacah.
Saya ingin membuktikan ke teman investor bahwa cerita sepanjang perjalanan tentang Sabang yang maatschapay bukan sekadar “bohay.”
Cerita yang dalam penyebarangan di lautan bebas itu saya kutip dari tulisan seorang wartawan hebat di sembilan puluhan tahun lalu yang terkagum-kagum dengan Sabang.
Sang wartawan bernama Adi Negoro. Adi Negoro yang membuat catatan perjalanan dari Batavia, Temasek, Sabang dan Eropa.
Kekagumam Adi Negoro di hari perjalanan saya dengan teman investor itu masih tersisa dalam gumam panjang.
Di luar pelabuhan. Di sebuah jalan kecil yang bersambung lagi ada kawasan yang saya katakan ke teman-teman itu sebagai “kampung Tionghoa.” Kampung Tionghoa yang kini jadi jalan perdagangan.
Laporannya perjalanan Sabang di era itu jadi sangat memikat karena Adi Negoro menggabungkan cerita sehari-hari dengan acuan berbagai bacaan klasik, dari antropologi hingga theologi, dari sejarah hingga filsafat.
Salah satu tempat pemberhentiannya adalah pelabuhan Sabang di Pulau Weh, di ujung Sumatra.
Ia menulis tentang persinggahan kapal tambora untuk mengisi bahan bakar batubara. Adi Negoro berkeliling Sabang.
Ia membandingkan Sabang dengan Singapura yang kala itu masih bernama Temasek milik Inggris yang baru saja disinggahinya.
“Tapi kalau menilik kepada pelabuhan saja, Sabang lebih bagus. Hanya perkara letaknya saja kurang baik.”
Lanjutnya,” biarpun pemerintah Belanda menjadikan Sabang satu pelabuhan bebas, tiadalah akan seramai Singapura, sebab letaknya jauh dari pusat perdagangan di Asia Timur.”
Di hari kunjungan saya itu Sabang masih dengan pohon morai. Pohon yang juga pernah ditulis oleh Adi Negoro. Pohon yang ditaksir berusia tiga ratus tahun.
Setahu saya Sabang memang hijau. Sehijau ketika dua teman karib saya bertugas jadi pejabat di Sabang dengan institusi yang berbeda. Institusi yang dulunya saling menyikut.
Menyikut lewat dua undang-undang yang setara tapi nggak sebangun.
Sabang memang hijau dengan pohon morai yang nama latinnya keluarga tumbuhan pithecellobium dulce. Tumbuhan yang banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara.
Konon, asalnya tanaman itu dari Amerika Tengah. Dalam bahasa Inggris-nya disebut guayamochil atau Manila Tamarind.
Saya menyebut nama tanaman itu asam Belanda lebih spesifiknya lagi asam koranji.
Pada zaman Adi Negoro, Singapura lebih besar dari Sabang, tapi perbedaannya kontras sekali hari ini. Singapura kini salah satu pelabuhan laut tersibuk dan termodern di dunia.
Sabang?
Ironis. Mengecil. Bahkan makin kurang pelayanannya dibanding ketika Adi Negoro datang di satu abad silam.
Singapura sekarang berpenduduk empat juta orang. Sabang nggak bergerak dari angka tiga puluh ribuan orang.
Teman saya yang pernah jadi Pj Wali Kota Sabang tahun lalu mengatakan bahwa pada era maatschapay Sabang memiliki dermaga dengan panjang total dua ribu tujuh ratus meter.
Sekarang hanya enam ratusan lebih. Lantas saya menyimpulkan Sabang mundur seratus tahun sejak era Roterdam Loyd
Bahkan teman yang lainnya, Zubir Syahim yang pernah jadi Ketua Badan Pengelola Kawasan Sabang, sering mengatakan Sabang masih punya prospek cerah sebagai hub lalu lintas perdagangan global.
Ia secara eksplisit sering memamerkan foto Sabang di era maatschapay di mana teluk indah itu mampu menampung hingga enam puluh kapal.
Sekarang berapa?
Ia nggak mengatakan pemerintah kurang memberi perhatian pada Sabang. Ia cuma membagi kenangan ketika dulunya derek peti kemas yang pertama ada di Sabang.
Sebelum ada di Singapura, Batavia atau Surabaya.
Keluhan tentang Sabang yang surut seratus tahun ke belakang bisa makin menjadi-jadi. Terutama ketika Sabang dibubarkan sebagai pelabuhan dan daerah perdagangan bebas.
Alasannya banyak “penyelundupan.” Tuduhan yang bisa dibantah termasuk oleh Zubir sendiri. Yang kemudian dipulihkan di awal abad ini dengan status bebas lagi.
Setiap kali saya mengunjungi Sabang bukan hanya karena kecantikan atau kekalahannya dari Singapura atau Batam. Atau pun yang terakhir ini oleh pulau pemping.
Tapi saya sungguh muak dengan permainan pemikiran politik. Sabang terletak di ujung paling barat dari negara yang dinamai Indonesia.
Frase ini sering dinamai dengan “Sabang-Merauke.” Frase yang juga sering disebut tiap kali Jakarta menghadapi pemberontakan daerah, termasuk Aceh.
Pemberontakan Aceh jadi terlihat paling serius. Untuk itu nggak harus dibiarkan merdeka.
Aceh dinyatakan darurat militer. Keputusannya yang dicatat oleh negara bernama Indonesia. Keputusan ini cukup populer mengingat meningkatnya rasa kebangsaan nun di tempat sana.
Seperti diketahui pemberontakan Aceh dilabel dengan GAM. Gerakan Aceh Merdeka. Sebuah jaringan gerilyawan yang mengupayakan pemisahan Aceh.
Yang saya mencatat di era itu ketika menjadi sesuatu di surat kabar lokal: kehadiran mereka sebenarnya tak begitu terasa di Sabang. Yang GAM-nya cuma puluhan dengan senjata api seadanya.
Dalam perjalanan ini teman investor yang saya pandu sempat terpesona dengan pemandangan cantik laut biru, ombak tenang, dan di kejauhan terlibat sebuah kapal kayu mungil.
Suara angin laut menderu-deru. Tempatnya sepi dan indah, terletak di balik sebuah bukit, dalam sebuah kawasan hutan lindung.
Ibaratnya, kata teman itu secara berbisik ke saya, negeri ini seperti selembar surga ditanamkan di muka bumi. Mereka jatuh cinta dengannya. Ada perasaan tenang, sendu, dan teduh.
Lantas saya berpikir, apa makna Indonesia ditempati?
Nasionalisme macam apa yang diinginkannya oleh mereka yang menelantarkan Sabang. Apa makna simbol ini ketika ketidakadilan pembangunan bersimbah darah.
Ketika Jakarta hanya melihat Batam, Pemping ataupun Rempang. Dan untuk apa Sabang-Merauke diberi nama keindonesiaan-indonesiaan.
Pemberian nama yang seakan-akan menggambarkan ada ikatan emosional antara semua warga “sabang” dan semua warga “merauke” nun jauh di ujung timur sana.
Lantas muncul pertanyaan saya, jika hubungan itu ada, mengapa ada pemberontakan besar di Aceh?
Mengapa banyak orang Aceh, seperti saya, setidaknya, menginginkan “otonomi khusus” atau bahkan “kemerdekaan”?
Saya merasa getir dengan setiap kali keputusan Jakarta yang membiarkan Sabang melata, mencabut status Pelabuhan Bebas Sabang dan sebagainya dan sebagainya?
Kemudiannya saya teringat literasi tentang “negara-bangsa.” Literasi tentang sebuah pemahaman tentang komunitas maya.
Sebuah komunitas yang sebenarnya adalah sebuah tempat di mana warganya tahu sebagian besar warga lain.
Dalam “negara-bangsa,” bahkan seumur hidup pun, seorang warga negara tak tahu sejumlah besar warga lainnya.Tak ada perasaan saling memiliki.
Saya tahu “bangsa” adalah sebuah proses, bukan sebuah produk. Proses inilah yang tampaknya kurang diperhatikan.
Kesibukan melakukan “pembangunan” dan mengatur semuanya dari sana, membuat Sabang terbengkalai dan membuatnya tidak membesar tapi mengecil.
Hujan pun turun rintik-rintik.
Praktis. Tidak lebih tidak kurang. Dan proses menjadi “bangsa” di negeri jadi gamang ketika merasa tujuannya sudah tercapai.[]
- Darmansyah adalah wartawan senior, penulis “Kolom Bang Darman”