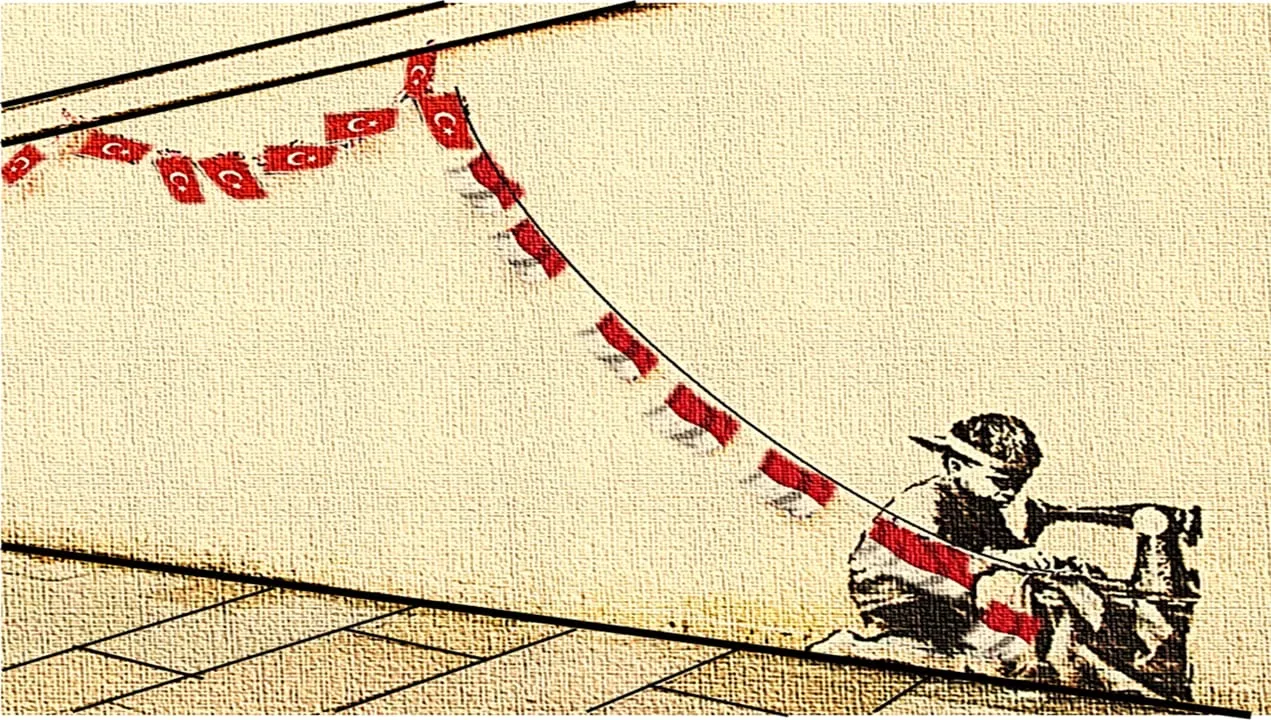Aceh Tak Memberontak, Ia Hanya Terluka
Oleh: Sri Radjasa, M.BA/Pemerhati Intelijen
SETIAP kali Aceh bersuara lantang, stigma lama kembali dihidupkan: separatis. Seolah-olah Tanah Rencong ini selalu ingin menjauh dari Indonesia. Padahal, jika kita jujur membaca sejarah, Aceh bukan sedang memberontak, melainkan sedang menuntut keadilan atas luka yang tak pernah benar-benar diobati oleh negara.
Aceh bukan daerah yang muncul bersamaan dengan republik ini. Aceh telah berdiri jauh sebelumnya sebagai kesultanan berdaulat, pusat peradaban Islam, dan kekuatan politik penting di Selat Malaka.
Dalam catatan sejarah dunia, Aceh dikenal sebagai bangsa yang disegani, bukan wilayah pinggiran yang bergantung pada belas kasihan kekuasaan lain. Kesadaran inilah yang masih hidup dalam ingatan kolektif orang Aceh hingga hari ini.
Ironinya, justru Aceh menjadi salah satu daerah paling setia saat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Dana, senjata, hingga dukungan diplomasi mengalir dari Aceh untuk republik yang masih rapuh. Namun kesetiaan itu dibalas dengan kebijakan yang melukai harga diri. Aceh dilebur ke dalam Sumatera Utara, pembangunan menjauh, dan ketika kekayaan alam Aceh dieksploitasi besar-besaran, yang tersisa bagi rakyat hanyalah ketimpangan dan kemiskinan struktural.
Dalam situasi seperti itu, perlawanan bukanlah pilihan ideologis, melainkan respons atas ketidakadilan. Negara sering lupa bahwa konflik lahir bukan dari niat buruk rakyat, melainkan dari kegagalan kekuasaan membaca jeritan di daerah.
Kemunculan Hasan Tiro pada 1976 bukan ledakan emosi sesaat. Ia adalah akumulasi dari kekecewaan panjang. Berbeda dengan perlawanan Darul Islam yang dibingkai agama, Hasan Tiro membawa narasi sejarah dan hukum internasional. Ia berbicara tentang Aceh sebagai bangsa yang pernah berdaulat dan haknya terputus oleh kolonialisme.
Gagasan successor state yang ia usung bukan sekadar romantisme masa lalu. Ia berdiri di atas argumentasi bahwa Belanda tidak pernah sah menaklukkan Aceh, dan karena itu tidak berhak menyerahkan Aceh kepada Indonesia melalui Perjanjian 27 Desember 1949.
Dalam kacamata hukum dekolonisasi PBB, kedaulatan berada di tangan rakyat wilayah jajahan, bukan di tangan penjajah. Di sinilah konflik Aceh berpindah dari medan senjata ke medan sejarah dan hukum.
Apakah seluruh rakyat Aceh sepakat dengan gagasan itu? Tidak. Namun gagasan tersebut menjelaskan mengapa konflik Aceh tidak pernah selesai hanya dengan operasi militer. Ia menyentuh martabat, identitas, dan harga diri sebuah bangsa yang merasa diabaikan.
MoU Helsinki 2005 seharusnya menjadi penutup luka. Senjata diturunkan, konflik dihentikan, dan Aceh diberi ruang mengatur dirinya sendiri melalui self-government. Partai lokal lahir, kewenangan diperluas, dan Aceh diberi kesempatan berdiri lebih bermartabat dalam bingkai Indonesia. Namun perdamaian bukan hanya soal kesepakatan, melainkan konsistensi dan empati.
Ketika pemerintah pusat kembali abai terhadap penderitaan Aceh, seperti dalam polemik penetapan status bencana nasional yang muncul bukan sekadar protes kebijakan, melainkan rasa ditinggalkan. Dari rasa itulah simbol-simbol lama konflik kembali muncul. Bukan karena Aceh ingin mengulang perang, tetapi karena Aceh merasa suaranya tak lagi didengar.
Aceh tidak bisa dibaca dengan pendekatan seragam. Seperti dikemukakan Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Aceh adalah ruang kesadaran. Melalui gagasan Acehnology, Aceh mengajak Indonesia untuk melihatnya sebagai subjek dengan nilai, sejarah, dan nalar sendiri. Membangun Aceh berarti mendengar Aceh, bukan sekadar mengatur Aceh.
Jika negara terus memandang Aceh sebagai daerah rawan dan bermasalah, luka itu akan terus terbuka. Tetapi jika Aceh diperlakukan sebagai mitra sejajar, Aceh justru akan menjadi penjaga paling setia di ujung barat Nusantara.
Aceh tidak pernah memberontak. Ia hanya terluka. Dan luka yang diabaikan, suatu hari akan kembali bersuara.[]