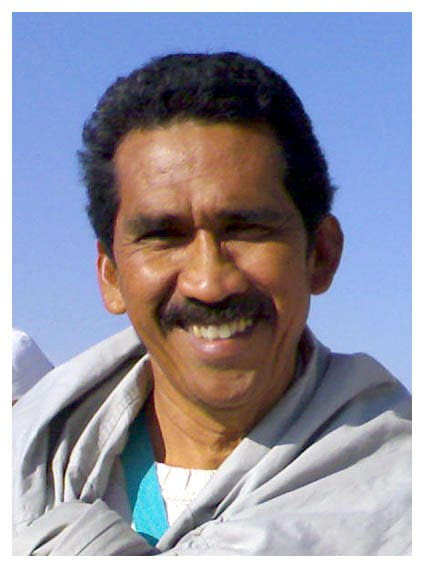Qanun Tersesat
BEGITU banyak qanun tersesat yang saya tahu dan baru tahu. Qanun yang lahir dari rahim legislasi di Aceh.
Qanun, yang padanan harfiahnya peraturan daerah. Popular dengan akronim perda.

Perda itu berada di bawah strata undang-undang. Undang-undang yang lahir dari gedung beratap bulat milik saingan grup lawak srimulat ..dulunya…
Yang saking hebat lawakan mereka di gedung beratap bulat mengalahkan tarzan, asmuni atau pun basuki. Dan srimulat pun bubar. Tapi grup lawak atap bundar itu tetap eksis.
Saya memakai kata “tersesat” untuk qanun dalam tulisan ini guna membedakannya dengan kata “menyesatkan.”
Dua kata yang kalau salah menempatkannya bisa menerjang ke kutub dakwa.
Saya nggak mau ada dakwa menempatkani satu akar kata. Akar kata sesat dan menyesat yang Anda sendiri dan saya so pasti tahu maknanya. Yang kata sesat pasti menyediakan jalan pulang.
Yang di era sekarang jalan pulang dari tersesat bisa lewat jemari dengan satu klik “google map”.
Kalau “menyesatkan?” Ini yang cilaka. Apalagi kalau ia ditabalkan ke ajaran. Ajaran menyesatkan…. Dan qanun yang perda itu tidak berada di ruang menyesatkan. Sebab ia bukan ajaran. Hanya peraturan.
Arti qanun sendiri seperti yang saya telusuri di wikipedia juga tidak menyesatkan. Cuma banyak yang bikin orang tersesat. Tersesat karena akar katanya. Yang diarabikan.
Padahal kata qanun itu sendiri muasalnya sangat panjang. Dari akar kata yunani. Diadopsi ke dalam bahasa turki dan diarabikan sebagai sebuah aturan. Bahkan qanun nyelonong ke akar kata inggris modern kanon.
Tak ada sakralitas di kata ini. Kata yang merujuk pada hukum yang dibuat oleh penguasa atau badan administrasi, ekonomi dan hukum pidana yang diundangkan sebagai hukum dinasti.
Dan qanun beda dengan syariah. Seperti yang menjadi qanun ekonomi syariah. Yang melipat bank-bank konvensional di Aceh. Tapi tak pernah melipat pokir yang membuat korupsi merajalela.
Kesejarahan qanun yang panjang ini pernah menimbulkan konflik kepentingan di tataran ekonomi. Konflik ketika qanun menjadi pembenaran di bawah penguasa.
Penguasa yang secana bersama membuat peraturan sendiri untuk kegiatan yang tidak ditangani oleh syariah. Konflik di ruang modern.
Yang banyak peraturan yang dicakup oleh qanun didasarkan pada masalah keuangan atau sistem pajak yang diadaptasi melalui hukum dan peraturan wilayah-wilayah.
Seperti yang terjadi di Aceh. Qanun yang menyebabkan seorang turis asing tak bisa membayar makan siang karena kartu kredit preimernya tak bisa menukarkan dolar ke rupiah di mesin atm.
Saya sendiri pernah menulis, dulu… beberapa tahun lalu, tentang qanun yang dilahirkan di ruang bisu.
Ketika resonansi qanun-qanun kontrovesial yang dikemas oleh legislatif provinsi untuk dijadikan produk peraturan daerah tidak melewati ruang terbuka. Ketika semua orang terkunci dalam satu kata, “apatis.”
Masa bodoh.
Apatisme yang tidak berarti diam. Tapi sebuah gumam dari ketidaksetujuan. Gumam terhadap produk yang mengabaikan etika multikultur, multietnis dan semangat egaliterian.
Pengabaian terhadap eksistensi minoritas dalam pasal-pasal qanun instusi dan simbol serta lambang provinsialis itu.
Pengabaian, yang seperti dibisikkan oleh seorang teman ketika kami berbincang “ringan.” mendegradasikan posisi subkultur dan subetnis pada posisi vertikal di tengah perkembangan tuntutan kesetaraan sebagai ciri moderenitas masyarakat terbuka.
Tidak hanya pengabaian, tapi juga pembangkangan terhadap ajaran kultural demokratis Aceh lama dengan falsafah, “meunyo ka meupakat lampoh ngon jirat tapeugala.”
Sebuah ajaran yang menempatkan kesepakatan bersama sebagai sebuah semangat perjuangan dan telah berdurasi panjang Teruji ketika melewati masa kritis dalam kehidupan sosial politik Aceh.
Dan ketika rancangan qanun-qanun itu dipakai sebagai sumber otoritas kelompok, institusi dan single authority dengann tameng sebagai kekuatan penekan, semua kita, sepertinya, merasa gamang untuk melakukan gugatan.
Kita gamang untuk berseberangan ketika perdebatan tidak memberi manfaat produktif. Tidak hanya publik yang diam.
Intelektual dan akademisi lebih senang melanjutkan sebagai “petapa” diam dan enggan turun mencampuri persoalan-persoalan nonsubstansial sebagai pencerahan. Semuanya bisu.
Parahnya lagi, ketika suara yang berkibar di seberang sana makin kencang dan mengeras, apatisme pun mengisi penuh ruang publik dengan mengutamakan penyelamatan diri.
Ruang publik yang selama ini digaduhkan oleh kelompok dan institusi independen seolah menjaga jarak untuk tidak menganggu safety yang selama ini lebih berharga dari mengedepankan egoismenya.
Pembahasan qanun-qanun itu, wali nanggroe, bendera dan lambang daerah, memang sedang menempuh jalan senyap untuk menghindar dari sentuhan publik serta dengan sengaja mengalpakan perdebatan di ruang terbuka.
Seperti polemik media, panel yang yang sering dilabeli el-es-em atau pun seminar sepenuh kamar atau setengah kamar yang bernuansa akademik dan diongkosi anggaran, seperti lazimnya sebuah undang-undang.
Kesenyapan itu makin meninggi intensitasnya bersamaan pula dengan adanya unsur kesengajaan untuk “mengorup” rancangan qanun-qanun itu dari sosialisasi ke entitas publik.
Sehingga, ketika resonansinya melintas di ruang terbuka ia menimbulkan reaksi keras ketika bergesekan dengan sentimentil minoritas.
Gesekan ini, seperti yang kita catat dalam beberapa aksi, mengundang debat kusir lewat kesenjangan multi tafsir dari orasi mau pun release berdurasi pendek dan menempatkan pihak-pihak, yang setuju dan menolak, dalam dua kutub yang saling “apriori.”
Kita tidak ingin mendalami substansi pasal-pasal dari qanun yang kontroversial itu. Kita hanya ingin menegaskan tentang hakekat manfaatnya bagi kelanggengan kehidupan majemuk dari masyarakat Aceh.
Untuk itu kita menyadari qanun-qanun, yang substansinya tidak menyentuh kesejahteraan rakyat secara absolut itu, dan tidak menjawab kebutuhan terkini prioritas masyarakat di negeri ini.
Sepertinya memang dipaksakan untuk siap pakai guna menampung hasrat prestise perjuangan, sekaligus memenuhi semangat megalomania tentang keterpisahan daerah ini sebagai sebuah federasi yang memiliki privelege.
Jalan sunyi di ruang publik ini, seperti kemudian kami selusuri, memang disengaja oleh banyak entitas dan komunitas yang selama ini memiliki kadar intelektualitas di atas rata-rata dalam mengisi ruang publik dengan membuka ruang perdebatan yang intens untuk kebaikan negeri.
Mereka, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, mencoba menghindar dari polemik yang sering sangat ir-rasional itu dan mencari posisi safety dalam memilih jalan sendiri-sendiri.
Mereka mengunci diri dari polemik yang dilontarkan spokesman wakil rakyat yang meretorikakan tentang perjalanan finalisasi draft qanun tanpa menginginkan respons berbeda.
Mereka tahu tentang argumentatif yang sengaja dikunci dari perspektif rancangan pasal-pasal peraturan itu. Mereka juga amat mafhum ketika dialog di ruang hampa bisa memunculkan kesimpulan-kesimpulan yang sangat argumentatif tentang manipulasi kata-kata.
Manipulasi tentang pembenaran bahwa rancangan qanun itu sudah dilemparkan ke ruang publik dan telah didiskusikan secara akademik. Tentang rancangan qanun yang yang sudah melewati ruang uji publik.
Atau pun pernyataan tentang tidak akan adanya perubahan jadwal pembahasan dan draft, yang dikatakan, sudah disepakati.
Kita menangkap ada penciptaan pembenaran di retorika mereka ketika kelemahan qanun diungkapkan secara rasional dengan mengacu pada hirarki peraturan dikaitkan dengan substansi yang menjadi dasar ia dibuat.
Substansi dari kesepakatan damai yang seharusnya dipertemukan kembali tafsirnya untuk kemudian dirujuk pada peraturan yang memayunginya.
Kita, mungkin sepakat, agar multitafsir dari kesepakatan damai yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh tentang rancangan qanun-qanun yang simbolis.
Kita juga menangkap ketidaksetujuan komunitas di belahan barat dan tengah Aceh yang merasa tidak nyaman dengan qanun-qanun yang ekslusif itu.
Tidak hanya mengalami penyumbatan dalam komunikasi, rancangan qanun-qanun itu seakan-akan mereka yakini sebagai pembenaran “anggapan” selama bertahun-tahun.
Kita tidak menginginkan adanya kebenaran yang menjadi stigmasisasi permanen. Yang kita inginkan adalah cairnya stigmasisasi ini sehingga tumbuh saling kepercayaan sebagai “tras” kebersamaan. “Tras” tentang kepemilikan bersama negeri majemuk kultur dan etnis ini.
Kita sudah belajar banyak dari konflik-konflik horisontal yang tak memberi keuntungan kepada golongan dan kelompok mana pun yang bertikai.
Kita menghendaki Aceh yang plural. Aceh yang tidak mengedepankan ego sektoral kedaerahan dan etnis sebagai alat untuk pembenaran.
Untuk itu kita perlu meluruskan jalan bagi lahirnya qanun-qanun simbolis dengan mengutamakan dialog terbuka, setara dan saling memahami kepentingan masing-masing tanpa harus bersitegang dengan pembenaran diri sendiri, kelompok atau lembaga.
Dibutuhkan ruang publik yang lebih terbuka untuk mendiskusikan persoalan-persoalan prestise ini. Ruang yang menyediakan jawaban secara nalar intelektual dan akademik.
Dan jangan ada di antara kita yang melakukan diskusi di ruang hampa dengan memanipulasi retorika yang berkecendurangan vertikal, “gertak” dan selalu sepihak seperti di masa amuk perang.
Kini, perdebatan tidak lagi bernuansa vertikal dengan prasyarat-prasyarat ketat, yang dulunya, sering memacetkan dialog.
Kini arena perdebatan sudah mengalami modifikasi bersamaan dengan suasana “romantisme pascaperang” yang sangat kasat suara.
Dan tidak harus lewat ancam mengancam seperti disuarakan secara sepihak dengan bunyi bahwa rancangan ini akan tetap jalan dengan pasal-pasal yang sudah ada.
Malah dengan nada tinggi para spoker itu mengatakan pembahasan draft itu sudah final. Entah di mana letak finalisasi. Entah sejak kapan ia selesai ditelaah.
Kita tidak pernah apriori dan memasang harga mati untuk mendiskusikan qanun-qanun, baik yang simbolis maupun yang bersubstansi kesejahteraan di ruang publik sepanjang ia dilabeli sebagai kepentingan bersama.
Kepentingan menyeluruh masyarakat Aceh.
Ruang publik tentu akan mengadopsi semangat “multikultur” dan “multietnis” karena itulah yang menjadi ciri masyarakat modern.
Masyarakat yang dibentuk dari kesetaraan plural yang menghindari “tirani” mayoritas maupun tirani minoritas. Masyarakat yang esensinya terbuka dengan mengedepankan akal sehat sebagai tujuan kepentingan bersama.
Kita tidak tahu apa tujuan dari pembentukan qanun-qanun, yang menurut pihak yang menentang saling bertabrakan dengan pasal-pasal peraturan pemerintah tentang lambang dan bendera yang menjadi acuan permainan di negara ini.
Acuan tentang semangat kemajemukan yang menempatkan kelompok dan personal secara garis lurus bukan tegak lurus.[]
- Darmansyah, wartawan senior, penulis “Kolom Bang Darman”