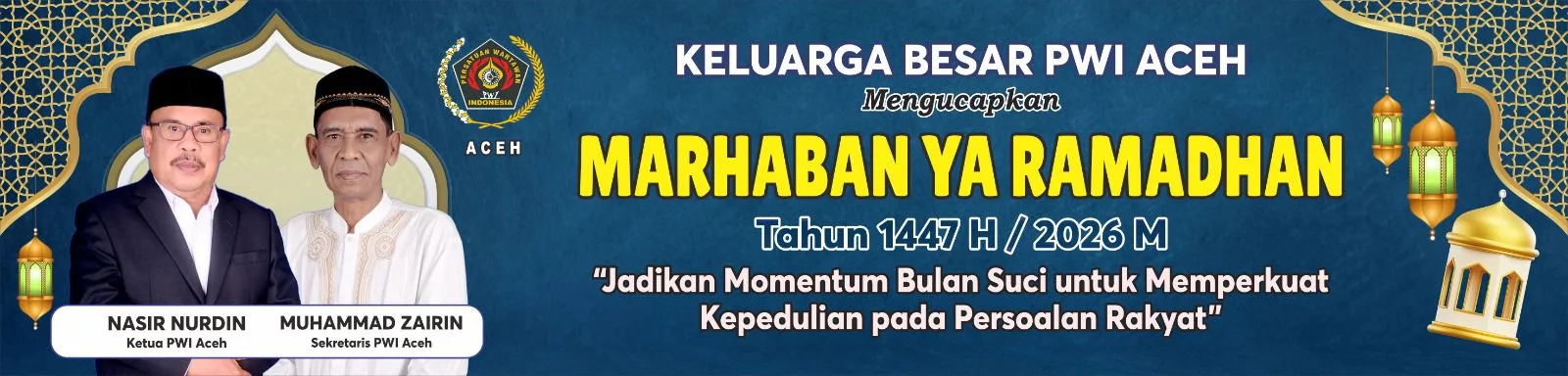Aceh; Satu Data untuk Siapa?
Oleh: TM Zulfikar/Pemerhati Sosial dan Lingkungan Aceh/Dosen Universitas Serambi Mekkah
DALAM kerangka reformasi birokrasi dan percepatan pembangunan berbasis bukti, inisiatif “Satu Data Aceh” sejatinya merupakan langkah progresif.
Ia berangkat dari kebutuhan mendesak akan integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi data lintas sektor.
Namun pertanyaan fundamental yang mesti diajukan adalah: apakah implementasi Satu Data Aceh benar-benar ditujukan untuk kepentingan publik luas, atau justru tersandera dalam ruang elitis birokrasi?
Teori pembangunan modern menekankan bahwa data yang valid, terbuka, dan dapat diverifikasi adalah prasyarat utama bagi pembuatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Tanpa data yang inklusif dan akuntabel, proses pengambilan keputusan berisiko menjadi spekulatif, tidak efektif, bahkan kontra-produktif.
Di konteks Aceh, kebutuhan akan satu data yang kredibel semakin urgen, mengingat kompleksitas persoalan sosial-ekonomi pasca-konflik dan pasca-tsunami yang masih berlapis hingga hari ini.
Sayangnya, praktik di lapangan menunjukkan bahwa Satu Data Aceh masih jauh dari ideal.
Alih-alih mendorong transparansi dan partisipasi publik, data justru kerap dikomodifikasi sebagai aset eksklusif birokrasi.
Permintaan terhadap data strategis, mulai dari angka kemiskinan aktual, peta kerentanan bencana, hingga status alih fungsi hutan, sering kali dibatasi dengan alasan “prosedur,” “keamanan data,” atau bahkan “kewenangan sektoral.”
Fenomena ini menciptakan paradoks: mengklaim satu data, namun mempraktikkan banyak kebenaran.
Ketidakselarasan antarsumber data resmi mengindikasikan lemahnya mekanisme verifikasi dan harmonisasi.
Ketika data kemiskinan dari satu instansi berbeda dengan data hasil sensus nasional, atau ketika data tata ruang pemerintah daerah tidak konsisten dengan peta nasional, publik berhak mempertanyakan integritas dari proyek Satu Data itu sendiri.
Secara epistemologis, data seharusnya menjadi sarana demokratisasi pengetahuan.
Di bawah prinsip open government, data publik wajib dapat diakses oleh siapa saja, kecuali yang menyangkut rahasia negara secara ketat.
Namun di Aceh, data acapkali dikelola secara oligarkis — menjadi sumber kekuasaan terselubung, bukan alat kontrol sosial.
Konsekuensinya sangat serius. Tanpa keterbukaan data, ruang publik kehilangan instrumen untuk melakukan pengawasan.
Tanpa akses data yang utuh, masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, hingga legislatif akan lumpuh dalam fungsi kontrolnya.
Pembangunan pun berjalan tanpa kritik yang sehat, mengarah pada potensi ketidakadilan distribusi program, pemborosan anggaran, dan kegagalan mencapai target-target kesejahteraan.
Dalam konteks ini, “Satu Data” seharusnya tidak dipahami sekadar sebagai proyek digitalisasi atau portal online.
Ia adalah kontrak sosial baru antara negara dan rakyat — di mana negara berkomitmen menyajikan informasi yang benar, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Aceh perlu menyadari bahwa modernitas pemerintahan tidak diukur dari jumlah aplikasi yang dikembangkan atau dashboard yang dipamerkan, melainkan dari sejauh mana data yang dikumpulkan dapat memperbaiki kehidupan masyarakat secara nyata.
Jika Satu Data Aceh gagal menjadi instrumen demokratisasi informasi, maka pada hakikatnya ia hanyalah alat kosmetik administratif — membangun citra tanpa substansi, menutupi defisit kepercayaan publik dengan gincu statistik.
Maka pertanyaan itu tetap sah untuk diajukan, dengan nada yang semakin tajam: Satu Data untuk siapa? Untuk rakyat, atau untuk membentengi kuasa? []